How the Online World Shapes Youth Identity and Well-Being
Kalau kita tanya anak muda soal “media sosial,” kebanyakan akan jawab hal itu bagian dari hidup sehari-har bukan dunia terpisah. Di sana mereka merakit cerita tentang diri, memilih foto yang terasa “gue banget,” menulis caption yang pas, lalu menimbang reaksi orang. Di balik itu, ada tiga hal yang terus saling berinteraksi pikiran, perasaan, dan tindakan. Pikiran menafsirkan apa yang kita lihat dan si teman yang selalu terlihat produktif, pasangan seleb yang tampak sempurna lalu perasaan ikut seperti perasaan bangga, iri, cemas, semangat. Setelahnya barulah tindakan ikut unggah target lari, mute akun yang bikin down, atau malah gabung kampanye sosial. Ilmu kognisi sosial memang sudah lama menjelaskan pola ini dimana kita cepat membuat makna tentang orang lain dan diri sendir dengan skema dan “jalan pintas” mental, yang kadang bias tapi efisien (Fiske & Taylor, 2017).
Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa media sosial memengaruhi kesejahteraan psikologis bukan karena lamanya waktu layar, tapi karena cara seseorang menggunakannya (Huang, 2017 ,Orben & Przybylski, 2019). Ketika orang muda memakai media untuk membandingkan diri dengan “kehidupan sempurna” orang lain, muncul perasaan cemas, iri, dan tidak cukup baik (Valkenburg & Peter, 2013). Tapi ketika media digunakan untuk berekspresi, terhubung, atau berbagi cerita yang bermakna, hasilnya justru positif rasa percaya diri meningkat dan identitas diri menjadi lebih kuat (Fiske & Taylor, 2017).
Fenomena ini juga terlihat dalam gerakan sosial anak muda. Cerita pribadi yang dibagikan di media sering kali menyulut gerakan besar. Menurut teori connective action, emosi seperti marah, empati, atau bangga dapat memicu keinginan untuk bertindak, dan media digital memberi ruang untuk menyalurkan energi itu menjadi aksi nyata (Bennett & Segerberg, 2012). Namun, tanpa keseimbangan, aktivitas digital bisa melelahkan karena terlalu banyak informasi, tuntutan tampil baik, dan tekanan untuk selalu aktif.
Jadi, bagaimana seharusnya kita menyikapi dunia digital ini? Kuncinya ada pada keseimbangan antara berpikir, merasa, dan bertindak. Pahami dulu bagaimana algoritma dan perbandingan sosial memengaruhi pikiran kita; belajar mengelola emosi yang muncul saat melihat postingan orang lain; lalu ubah kebiasaan digital agar lebih sehat misalnya membatasi waktu scroll, memilih akun yang membawa semangat positif, atau menulis hal yang jujur tentang diri sendiri. Pendekatan ini bukan soal berhenti main media sosial, tapi belajar hidup lebih sadar di dalamnya.
Daftar Pustaka :
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Information, Communication & Society, 15(5), 739–768. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.67066
- Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (2017). Social cognition: From brains to culture (3rd ed.).SAGE Publications Ltd.
- Huang, C. (2017). Time spent on social network sites and psychological well-being: A meta analysis. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 20(6), 346–354. https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0758
- Orben, A., & Przybylski, A. K. (2019). The association between adolescent well-being and digital technology use. Nature Human Behaviour, 3, 173–182. https://doi.org/10.1038/s41562-018-0506-1
- Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2013). The differential susceptibility to media effects model. Journal of Communication, 63(2), 221–243. https://doi.org/10.1111/jcom.12024
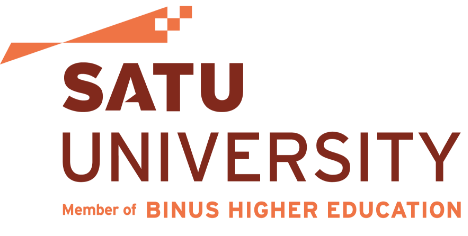

Comments :