Langkahku Menjaga Tubuh dan Merawat Masa Depan Mereka melalui Psikoedukasi Sedini Mungkin
Pagi itu, 16 Januari 2025. Udara terasa lembap saat langkah kaki ini bersisian dengan Bu Yulita, dosen di kampusku sekaligus psikolog anak. Hari itu, peran yang diemban bukan lagi mahasiswa di dalam kelas, melainkan fasilitator psikoedukasi sex education untuk siswa SD kelas 1-3. Meski tugas utama hanya membawakan ice breaking dan nyanyian sederhana, telapak tanganku terasa dingin dan sedikit lembap. Jemari berkali-kali meremas satu sama lain, mencoba mengusir rasa gugup yang membuat perut sedikit mulas. Pikiranku mulai kemana mana, takut gerakannya kaku, takut salah bicara, atau lebih buruk lagi, mempermalukan nama almamater di depan sekolah.
Ketegangan baru sedikit mencair saat tiba di aula. Dari ambang pintu, Anak-anak kecil itu masuk satu per satu dengan senyum yang merekah. Beberapa menyapa dengan senyum lebar, sementara yang lain melambaikan tangan dengan malu-malu. Sangat lucu. Melihat binar mata tanpa beban itu, rasa takut perlahan berganti menjadi antusias.

Acara dimulai. Bu Yulita membuka sesi, seperti seorang kakak perempuan yang sedang mendongeng, “Apa sih bedanya laki-laki dan perempuan?” tanya beliau. Seketika, aula riuh. Jawaban-jawaban jujur dan polos berebutan keluar dari mulut-mulut mungil itu. Ada yang menjawab soal rambut, ada yang soal pakaian. Dari titik itu, Bu Yulita mulai materi yang sangat krusial yaitu area prbadi. Penjelasan beliau mengalir, memilih kata-kata sederhana untuk menjelaskan bahwa ada bagian tubuh yang “eksklusif” di balik pakaian dalam yang tidak boleh disentuh atau dilihat siapa pun. Beliau juga memperagakan cara berteriak “TIDAK!” dan lari sekuat tenaga jika ada ancaman. Saat giliranku tiba, langkah kaki maju ke depan aula. Tarikan napas panjang diambil untuk menenangkan detak jantung yang masih berpacu. Lagu tentang sentuhan boleh dan tidak boleh pun mulai dinyanyikan. “Sentuhan boleh… sentuhan boleh…” sambil memperagakan gerakan tangan menyentuh kepala dan kaki.

Melihat puluhan anak berdiri dan mengikuti gerakan secara serempak, tangan-tangan kecil yang bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti irama, rasa senang menjalar ke seluruh tubuh. Mereka ikut bernyanyi dan bergerak aktif, di saat yang sama, sebuah pemahaman baru sedang ditanamkan ke kepala mereka. Sesi tanya jawab menjadi momen paling berkesan sekaligus menantang. Keluguan mereka membuat pertanyaan yang muncul seringkali melompat jauh dari materi. Seorang anak perempuan tiba-tiba bertanya dengan wajah serius kepadaku,”Kak, katanya laki laki nggak boleh make-up, kok abang aku pakai make-up?”
Aku sempat tertegun. Otakku berputar cepat mencari kata yang tepat. Butuh waktu hampir sepuluh menit bagiku untuk menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, mencoba membedakan konteks tanpa membingungkan logika mereka yang masih sangat konkret. Benar kata teori perkembangan, berbicara dengan anak seusia ini tidak bisa pakai bahasa langit. Harus jelas, nyata, dan terbayang di pikiran mereka. Saat perjalanan pulang, hatiku dipenuhi rasa hangat yang sulit dijelaskan. Tapi, perasaan itu hanya bertahan sejenak sebelum berubah menjadi kekhawatiran. Aku memandangi foto – foto mereka saat sesi tadi, “Bagaimana jika mereka mengalami pelecehan dan mereka tidak sadar bahwa itu adalah kejahatan?”, “Apakah mereka akan benar-benar berani lari seperti yang diajarkan Bu Yulita?”
Pikiranku mendadak gelisah. Apalagi aku tahu data Kemenpppa 2025 menempatkan Jawa Barat di peringkat pertama kasus pelecehan. Rasanya miris mengingat sex education masih sering dianggap tabu oleh orang tua, dan hanya diajarkan di sekolah saat sudah masuk masa pubertas, yang sebenarnya sudah sangat terlambat. Aku tidak sanggup membayangkan senyum manis anak-anak tadi berubah menjadi trauma yang menghancurkan masa depan mereka begitu saja. Beberapa bulan berlalu, aku menjadi bagian Himpunan Psikologi. Saat rapat pembentukan program kerja Himpunan, aku memberanikan diri mengajukan topik sex education. Aku tidak datang dengan deretan data, melainkan berbagi cerita tentang pengalaman dan perasaanku saat mendampingi Bu Yulita waktu itu. Mereka tertarik. Kemudian salah satu dari kami melakukan riset data pendukungnya, dan hasilnya memang menunjukkan urgensi yang tinggi. Kami pun sepakat. Saat dipresentasikan di depan pembina, proker ini pun langsung mendapatkan persetujuan.

Materi kami susun dengan teliti, memastikan setiap kata sesuai dengan tahap perkembangan siswa kelas 3-4 SD. Sekolah pertama kami adalah SD Kalam Kudus. 28 November 2025, kali ini aku yang berdiri di depan sebagai pembicara, sementara adik tingkatku menjadi fasilitator.
Sepanjang menjelaskan, kakiku sempat sedikit gemetar, sesinya hampir sama seperti sesi Bu Yulita tapi sekarang aku banyak menyelinginya dengan interaksi. Jawaban-jawaban mereka yang cerdas membuat rasa banggaku naik satu tingkat. Harapanku juga meningkat, semoga pengetahuan ini menjadi perisai bagi mereka.


Bukan hanya kepada siswa aku menaruh bangga, tapi juga kepada teman temanku, setelah sesi aku menanyakan bagaimana kesan mereka, dan jawaban mereka persis seperti perasaanku waktu itu, seru.
Pulang dari sekolah tak ada hentinya kami membicarakan bagaimana pengalaman kami di sana, bagaimana anak laki laki lebih semangat, bagaimana anak perempuan lebih banyak pertanyaan, dan bagaimana cara kami menjawab. Ada satu hal lain yang aku sadari, ternyata bukan hanya para siswa yang terbantu, tapi aku sebagai mahasiswa Psikologi justru mendapatkan jauh lebih banyak. Aku belajar memahami dunia dari kacamata mereka, hal yang membuatku merasa jauh lebih luwes saat harus berinteraksi dengan anak-anak setelah ini.
Lebih dari sekadar pengalaman lapangan, momen ini membuatku belajar lebih menghargai diriku sendiri. Ada rasa bangga yang indah saat menyadari bahwa kehadiranku ternyata membawa arti nyata bagi mereka, sekaligus menjadi kontribusi tulus bagi Hima.
Dokumentasi kegiatan:




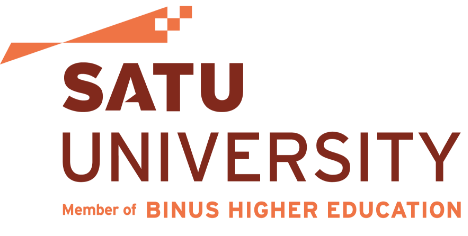

Comments :